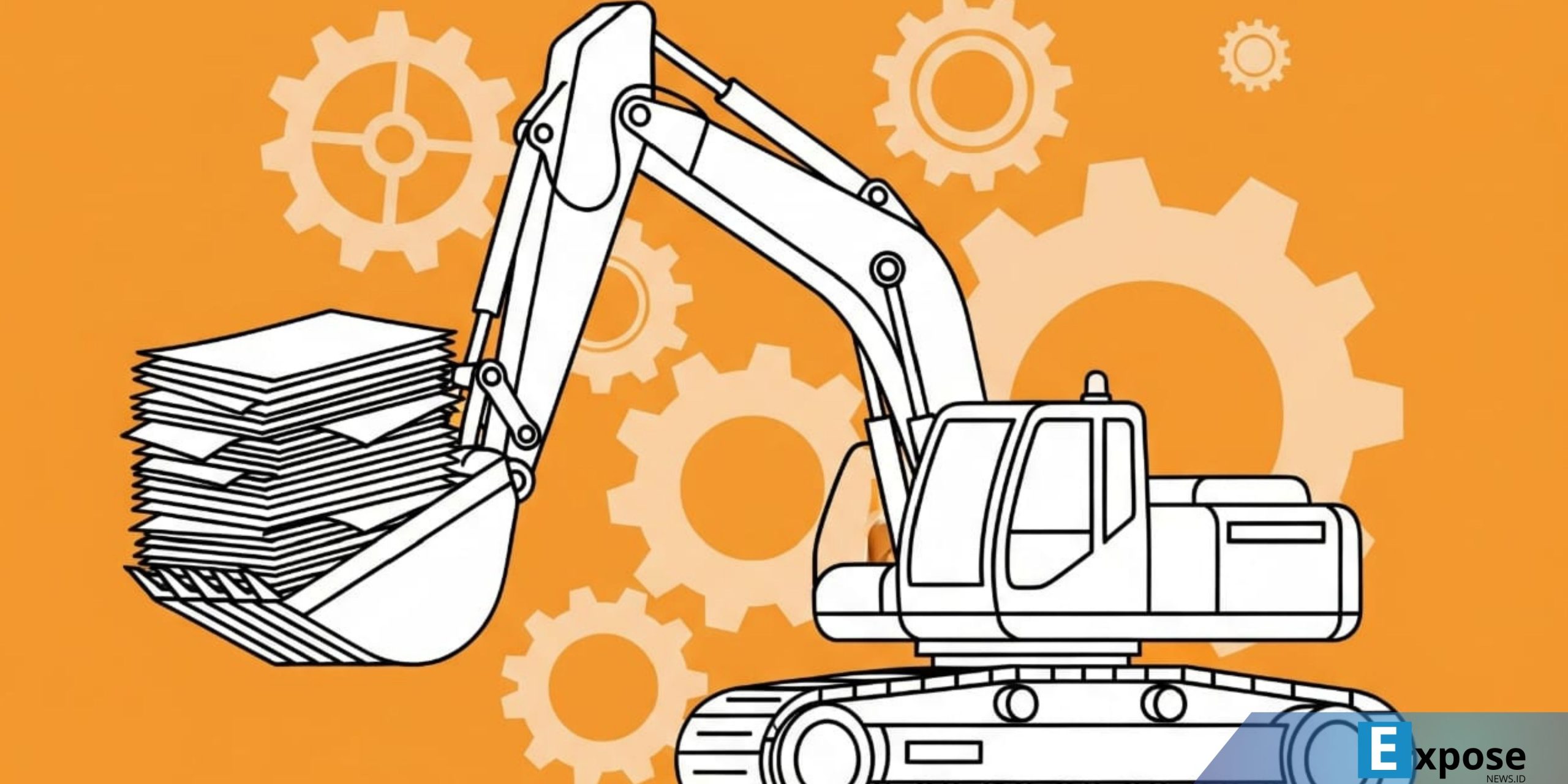Exposenews.id – Kontroversi izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, memicu perdebatan sengit antara legalitas dan legitimasi. Pemerintah baru saja mencabut izin empat perusahaan tambang karena melanggar aturan lingkungan dan masuk kawasan geopark. Namun, izin PT Gag Nikel—yang sebagian sahamnya dimiliki negara—masih berdiri kokoh. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beralasan, keputusan ini mempertimbangkan faktor hukum, sejarah, dan hasil verifikasi lapangan. PT Gag juga disebut sudah menyiapkan rencana kerja dan anggaran sebagai syarat izin.
Konstitusi vs Praktek Tambang: Ada yang Salah?
UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 jelas menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, konstitusi mewajibkan negara untuk menguasai sumber daya alam dan menggunakannya sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Artinya, semua izin tambang wajib mematuhi mandat ini. Sayangnya, realitanya berbeda.
Dalam hukum administrasi, izin tambang seharusnya bukan sekadar dokumen formal, tapi alat untuk mengatur, membina, dan mengawasi eksploitasi sumber daya alam. Namun, konflik di Raja Ampat membuktikan bahwa banyak izin tambang hanya kuat di atas kertas, tapi lemah di mata masyarakat.
Legalitas vs Legitimasi: Dua Dunia yang Berbeda
Legalitas berarti izin tersebut sah secara prosedur dan memenuhi syarat administratif. Tapi legitimasi menuntut lebih—masyarakat harus menerimanya secara moral dan sosial sebagai praktik yang adil. Banyak izin tambang memenuhi syarat hukum, tapi gagal dapat legitimasi karena mengabaikan partisipasi masyarakat adat, merusak lingkungan, dan melanggar hak ulayat.
Di Raja Ampat, PT Gag Nikel mungkin legal, tapi tidak legitimate. Buktinya, warga adat Waigeo Barat terus memprotes kehadiran tambang ini. Perusahaan tambang mengeruk nikel dari tanah mereka, sengaja mengabaikan protes warga.
Pencabutan Izin Tambang: Solusi atau Sekadar Pencitraan?
Presiden Prabowo Subianto memang mencabut empat izin tambang di Raja Ampat. Tapi alasan pencabutannya hanya soal pelanggaran prosedur, bukan pengakuan hak masyarakat adat. Itu sebabnya pemerintah melindungi izin PT Gag—karena menilai perusahaan ini ‘taat aturan’. Padahal, aturan itu sendiri mengabaikan fakta bahwa Pulau Gag merupakan tanah adat yang wajib mereka lindungi.
Masalah yang Terulang: Dari Raja Ampat Sampai Kalimantan
Praktik eksploitasi tanpa legitimasi bukan cuma terjadi di Raja Ampat. Di Halmahera Tengah, Maluku Utara, warga adat Sawai dan Tobelo Dalam berjuang melawan tambang nikel yang merusak lingkungan. Di Kalimantan Tengah, masyarakat Laman Kinipan berkonflik dengan perusahaan sawit sejak 2011. Bahkan aparat menangkap tokoh adat itu hanya karena ia mempertahankan tanah leluhurnya.
Tanah Bukan Cuma Properti, Tapi Ruang Hidup
Korporasi dan pemerintah memandang tanah hanya sebagai komoditas yang bisa mereka eksploitasi untuk keuntungan. Tapi bagi masyarakat adat, tanah adalah ruang hidup, spiritualitas, dan identitas. Teori Henri Lefebvre dan David Harvey menyebut, ruang selalu mencerminkan kepentingan kelompok dominan. Dalam sistem kapitalisme neoliberal, negara dan korporasi bekerja sama menciptakan ruang untuk keuntungan, bukan untuk kehidupan sosial.
Mereka menjalankan skema accumulation by dispossession—dengan paksa merampas tanah rakyat. Negara yang seharusnya netral, justru ikut mendorong pengusiran warga adat. Padahal, merekalah yang paling berhak menentukan nasib tanah mereka.
Protes Warga Adat: Tanda Kegagalan Legitimasi
Ketika warga adat memprotes, itu pertanda jelas bahwa aktivitas tambang dan perkebunan tidak legitimate. Perusahaan mungkin punya izin resmi, tapi tanpa persetujuan sosial, keadilan tidak pernah terwujud. Alam pun terus terkikis, sementara masyarakat adat semakin terpinggirkan.
Solusi yang Harus Segera Dijalankan
Pertama, pemerintah harus segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat dengan melibatkan partisipasi aktif warga. Tanpa pengakuan hukum yang jelas, pihak-pihak kuat akan terus mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Kedua, pemerintah perlu memetakan wilayah adat ke dalam peta resmi negara melalui proses partisipatif bersama masyarakat setempat. Jika tidak, korporasi dan oknum akan terus menganggap tanah adat sebagai wilayah tak bertuan dan mudah mereka rampas.
Jika pemerintah terus mengandalkan legalitas semata tanpa memperjuangkan legitimasi, konflik akan terus terjadi. Masyarakat adat semakin menderita, alam semakin rusak, dan keadilan hanya jadi mimpi.
Hukum yang mengabaikan keadilan substansial hanya melahirkan kekuasaan tanpa legitimasi. Raja Ampat hanyalah satu contoh dari banyaknya konflik tambang di Indonesia. Sudah saatnya negara hadir bukan hanya sebagai pemberi izin, tapi sebagai pelindung rakyat dan alamnya.
Baca Juga: Oknum Polisi di Bangkalan Diduga Gelapkan Uang Rp 60 Juta Tetangga